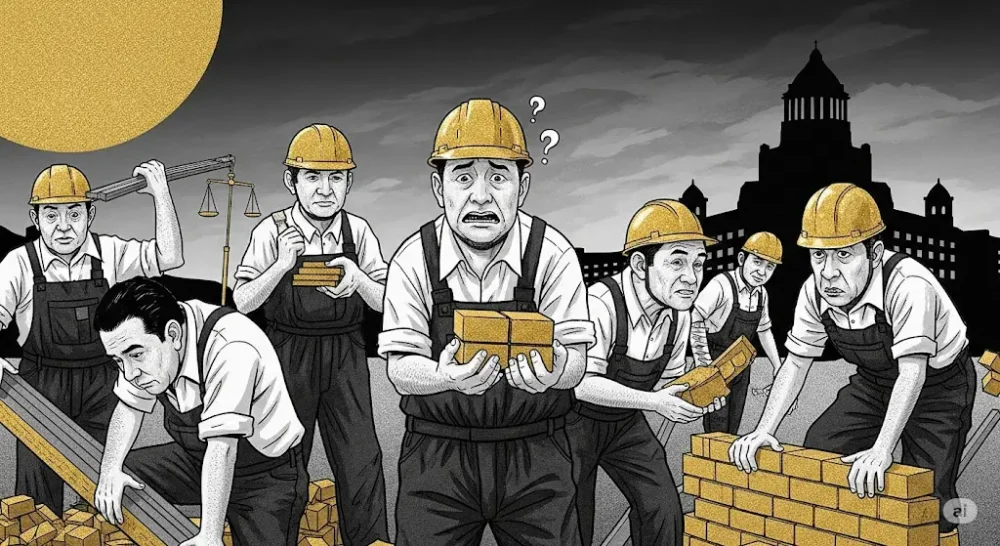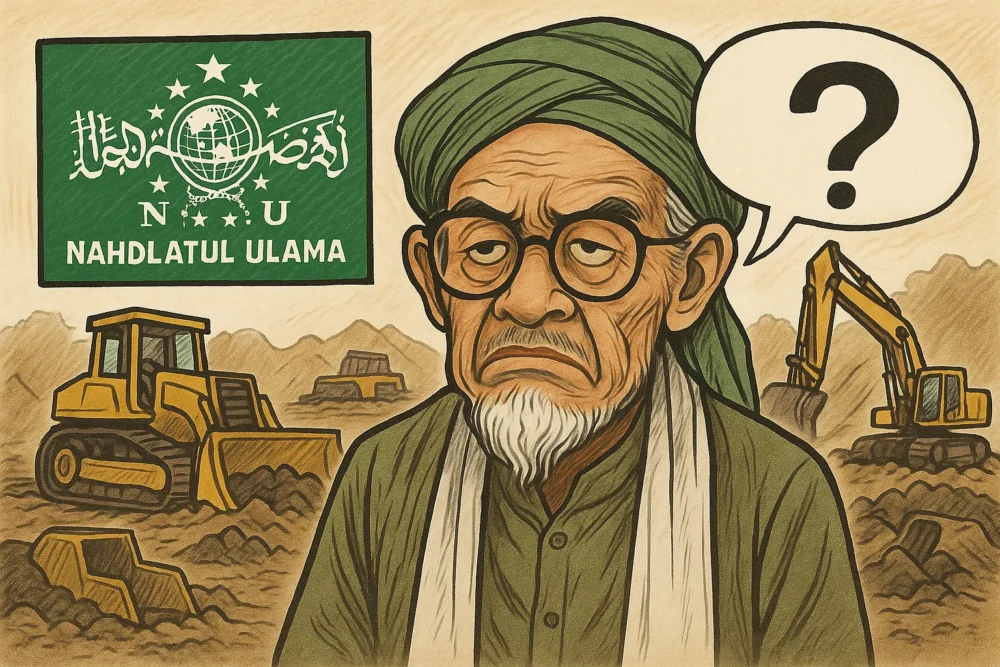Budaya literasi kita menyerupai lelucon tragis yang terus dipentaskan tanpa refleksi. OECD membeberkan fakta pahit bahwa lulusan S-1 Indonesia tertinggal jauh dari siswa SMP negara maju dalam hal kemampuan membaca kritis. Ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bukti kegagalan sistem yang memuja formalitas di atas substansi.
Lihatlah kampus-kampus kita—megah secara fisik, tetapi miskin secara intelektual. Perpustakaan dipenuhi buku usang era 80-an, sementara akses ke jurnal internasional masih jadi mimpi. Mahasiswa dicekoki modul usang yang lebih pantas jadi arsip museum, sementara dunia di luar sudah berlari dengan quantum computing dan AI ethics.
Sistem pendidikan kita bagai teater absurd, kurikulum dirancang untuk memproduksi penghafal, bukan pemikir. Ujian akhir tak lebih dari ritual pilihan ganda yang mengukur daya ingat, bukan kecerdasan. Dosen-dosen, terjepit antara tuntutan birokrasi dan beban mengajar, lebih sering menjadi tukang nilai ketimbang mentor yang membuka wawasan.
Di Finlandia, anak SMP diajak merancang eksperimen sains sederhana; di sini, mahasiswa teknik masih berkutat menghafal rumus tanpa pernah diajak memahami konteks aplikasinya. Hasilnya? Gelar sarjana hanya jadi simbol status, bukan jaminan kapasitas analitis.
Masalahnya merambah ke ranah kebijakan. Anggaran pendidikan yang digemborkan sebagai solusi, nyatanya dikelola dengan mentalitas korup. Dana yang seharusnya membeli buku, melatih guru, atau membangun infrastruktur digital, lenyap dalam proyek-proyek fiktif dan studi banding tak jelas.
Alih-alih mengejar ketertinggalan, kita justru memperdalam jurang ketimpangan. Di Singapura, siswa SMP dikenalkan pada machine learning melalui laboratorium canggih; di Indonesia, komputer di sekolah-sekolah pedalaman masih menggunakan Windows XP—jika ada.
Guru dan dosen, ujung tombak pendidikan, menjadi korban sekaligus pelaku kemandekan ini. Mereka diharapkan menjadi agen perubahan, tetapi dibelenggu sistem yang memaksa mereka mengajar dengan metode kuno. Pelatihan pedagogi? Hanya formalitas belaka.
Gaji yang tak sepadan dengan beban kerja memaksa mereka mencari penghasilan tambahan, alih-alih fokus mengembangkan kreativitas mengajar. Di Denmark, guru SMP digaji setara insinyur berpengalaman; di sini, guru honorer bertahan dengan upah yang tak cukup untuk membeli buku berkualitas.
Budaya baca yang lemah memperparah keadaan. Rata-rata orang Indonesia membaca 2-3 buku per tahun—angka yang memalukan dibandingkan negara-negara Skandinavia yang mencapai 10-15 buku. Tapi jangan buru-buru menyalahkan masyarakat.
Ketika akses ke bacaan bermutu terhalang harga mahal dan minimnya perpustakaan, bagaimana minat baca bisa tumbuh? Kampus-kampus lebih bangga menggelar seminar bertema bombastis ketimbang menyediakan akses ke platform seperti JSTOR atau ScienceDirect. Mahasiswa akhirnya mengandalkan handout fotokopian yang isinya tak pernah diperbarui sejak era reformasi.
Teknologi pendidikan kita pun tertatih-tatih. Di Korea Selatan, siswa SMP sudah akrab dengan coding dan analisis data real-time; di sini, “literasi digital” direduksi menjadi kemampuan mengisi Google Form.
Kampus berlomba mengadopsi jargon e-learning, tetapi infrastruktur internetnya lebih lambat dari kecepatan kuda penarik delman. Ironisnya, kita menyebut ini “kemajuan”, padahal yang terjadi hanyalah ilusi—seperti membangun menara pencakar langit di atas fondasi lumpur.
Reformasi? Pemerintah gemar mengumumkan program baru dengan embel-embel “revolusioner”, tetapi implementasinya selalu setengah hati. Dana digelontorkan untuk pelatihan guru yang isinya sekadar ice breaking dan foto bersama.
Kurikulum dirombak setiap 5 tahun, tetapi esensinya tetap sama! hafalan, hafalan, dan hafalan. Kita seperti pasien yang terus mengganti dokter, tetapi menolak minum obat.
Jika ingin keluar dari kubangan ini, kita harus berani membongkar mentalitas instan. Pendidikan bukan tentang mencetak sarjana bergelar, melainkan membangun manusia yang mampu berpikir mandiri. Hapuskan ujian yang mengukur hafalan, ganti dengan proyek kolaboratif yang menantang logika.
Berdayakan guru dengan gaji layak dan pelatihan bermutu, bukan sekadar sertifikasi kosong. Dan yang terpenting, akui bahwa masalah literasi bukan sekadar urusan sekolah, melainkan cermin kegagalan kolektif sebagai bangsa.
Tanpa perubahan radikal, kita akan tetap jadi bangsa yang gemar berkoar tentang “SDM unggul”, sementara anak-anak kita tumbuh jadi generasi yang fasih bermain TikTok, tetapi gagap menganalisis teks sederhana. Gelar sarjana akan tetap jadi simbol prestise semu—seperti patung emas yang berkilau di luar, tapi keropos di dalam.