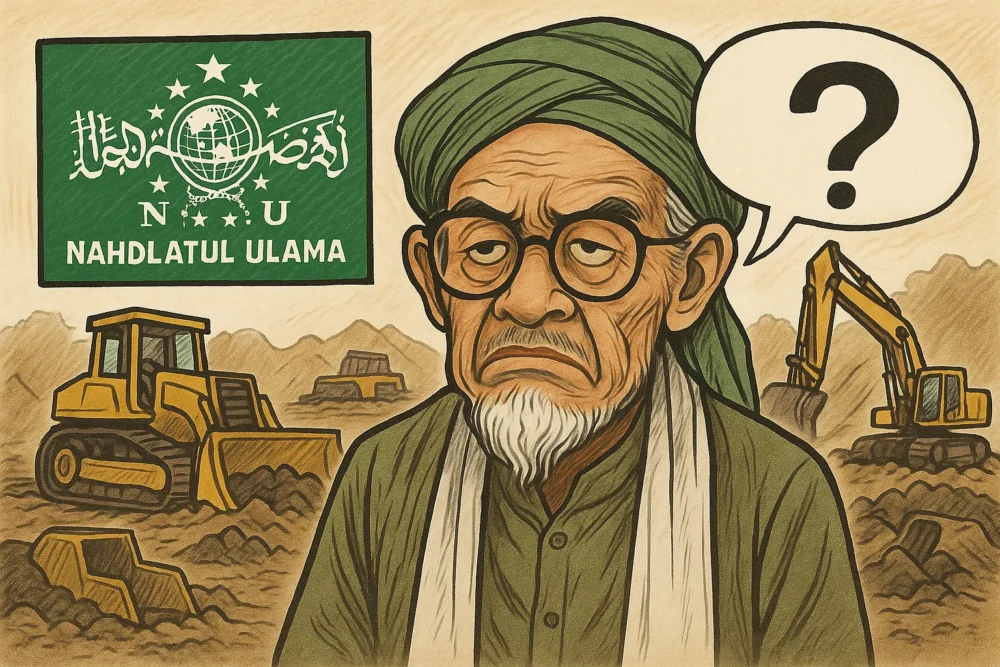Bayangkan dunia ini seperti panggung teater kolosal, dengan panggung megah di Tiongkok dan sutradara utamanya adalah Mao Zedong. Salah satu pertunjukan terbesarnya adalah Revolusi Kebudayaan yang berlangsung dari 1966 hingga 1976.
Tapi bagaimana jadinya kalau Mao sedang demam waktu itu dan melewatkan jadwal launching revolusi ini? Atau andai saja ia lebih tertarik bercocok tanam bonsai daripada membakar buku Konfusius? Nah, dalam semangat berpikir ala “What If…” mari kita tengok dunia alternatif tempat Revolusi Kebudayaan tidak pernah terjadi, dan menyaksikan betapa lucu sekaligus kacaunya sejarah jika jalurnya diputar ke arah lain.
Tanpa Revolusi Kebudayaan, besar kemungkinan Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping, dua tokoh pragmatis dalam Partai Komunis Tiongkok (PKT), naik pangkat lebih cepat. Mereka membawa konsep “sanzi yibao” yang pada intinya adalah bentuk early access kapitalisme. Dalam semesta ini, petani boleh punya tanah, pasar kecil boleh eksis, dan jual-beli bebas nggak harus sembunyi-sembunyi. Tapi ini bukan berarti semuanya jadi bahagia seperti akhir film kartun.
Justru menurut teori Marxis, ini bisa memunculkan kelas sosial baru yang bikin suasana makin panas. Petani bisa mulai beli traktor sendiri, buruh desa bisa ngerasa tertinggal, dan dalam waktu singkat, muncul drama sosial yang bisa bikin Karl Marx bangkit dari kuburnya sambil ngomel, “Lho, kok gitu cara mainnya?”
Lebih lanjut, tanpa Revolusi Kebudayaan yang mengganyang habis-habisan apa yang disebut Mao sebagai “Empat Lama” — yaitu pikiran lama, budaya lama, kebiasaan lama, dan tradisi lama — struktur sosial yang feodal dan penuh simbol-simbol klasik bisa tetap bertahan. Konfusianisme yang dulu dicap sebagai racun ideologis oleh Red Guards, mungkin malah berkembang jadi program unggulan di universitas.
Bayangkan, kalau Konfusius hidup di dunia alternatif ini, dia mungkin sudah punya kanal YouTube dengan jutaan subscribers yang membahas “cara menjadi anak berbakti dengan gaya milenial”. Nilai-nilai keluarga ala Tiongkok kuno bisa tetap jadi kiblat, bahkan mungkin memengaruhi sistem birokrasi dan pendidikan. Sayangnya, ini juga bisa membuat transformasi menuju masyarakat sosialis jadi setengah matang. Ibarat mie instan yang dimasak tanpa air—kebijakan terlihat modern, tapi cita rasa masih jadul.
Urusan pendidikan juga bisa berubah drastis. Kita tahu bahwa Revolusi Kebudayaan menutup sekolah dan mengirim para dosen serta pelajar untuk “belajar dari rakyat” di desa-desa, sering kali sambil mencangkul sawah.
Tapi tanpa gerakan ini, pendidikan mungkin tetap jalan… tapi eksklusif. Anak pejabat dapat akses ke sekolah bagus, sementara anak petani disuruh belajar dari majalah bekas dan radio rusak. Tidak ada upaya besar-besaran untuk meratakan kesempatan belajar. Akibatnya? Ketimpangan antara kota dan desa makin melebar, kayak selisih harga antara kopi sachet dan kopi artisan.
Teknologi dan inovasi juga terkena imbasnya. Meskipun Revolusi Kebudayaan sempat membuat ilmuwan lebih sibuk menyusun slogan daripada riset, dalam semesta alternatif ini, stagnasi justru bisa bertahan lebih lama. Tanpa tekanan ideologis yang memaksa semuanya berubah—meskipun lewat cara brutal—para pemimpin mungkin enggan berinvestasi di riset dan pengembangan.
Mereka bisa saja tetap nyaman dengan model ekonomi agraris sambil berharap traktor bisa diperbaiki dengan doa. Revolusi Industri versi Tiongkok pun bisa terlambat bertahun-tahun, dan dunia bisa kehilangan pesaing terbesar dalam industri robot dan ponsel pintar. Siapa tahu, kalau Revolusi nggak pernah terjadi, hari ini kita masih pakai pager buatan lokal dan nonton televisi tabung sambil nyetel lagu propaganda.
Di dalam tubuh PKT sendiri, absennya Revolusi bisa bikin suasana internal semakin panas. Mao menggunakan gerakan ini untuk menyingkirkan rival-rivalnya—semacam politik kantor, tapi versi hardcore. Kalau tidak ada itu, maka berbagai faksi dalam PKT mungkin akan berebut kekuasaan secara terbuka.
Drama adu strategi antara faksi Maois dan faksi reformis bisa bikin sinetron jam prime time kalah seru. Teori politik menyebut ini sebagai situasi rentan terhadap fragmentasi kekuasaan. Mungkin saja terjadi kudeta kecil-kecilan di dalam partai, atau bahkan pecah kongsi seperti boyband yang sudah terlalu lama tampil bareng. Rakyat? Ya bingung harus ikut siapa, sementara harga beras bisa melambung karena inflasi politik.
Dari sisi budaya, masyarakat Tiongkok yang tidak mengalami Revolusi Kebudayaan mungkin menghadapi benturan identitas. Di satu sisi, ada warisan tradisi ribuan tahun yang masih hidup, seperti nilai-nilai Konfusianisme dan ritual leluhur. Di sisi lain, ada semangat sosialisme modern yang ingin membentuk manusia baru yang patuh pada negara dan punya semangat kolektif.
Tanpa pemaksaan identitas proletar seperti di masa Revolusi, masyarakat bisa mengalami semacam disonansi budaya. Orang-orang bingung: mau sembahyang leluhur atau ikut rapat RT tentang koperasi bersama? Mungkin saja akan muncul generasi yang membaca buku Mao di pagi hari, lalu mendalami ajaran Taoisme di malam hari. Campur aduk, kayak minuman soda dicampur teh.
Hal lain yang menarik, kelompok minoritas seperti Tibet dan Mongolia Dalam mungkin lebih berani bersuara. Tanpa tekanan dan represi ekstrem selama Revolusi, tuntutan otonomi bisa terdengar lebih keras. Bisa jadi, mereka mulai menyuarakan identitas etnis dan budaya sendiri, lalu muncul gerakan separatis.
Dan karena dunia luar—terutama Uni Soviet atau bahkan India—senang melihat Tiongkok repot sendiri, dukungan terhadap kelompok-kelompok ini bisa muncul diam-diam. Bayangkan jika Tibet mengadakan festival kemerdekaan tahunan dan jadi tujuan wisata spiritual kelas dunia. Pemerintah pusat tentu akan kebingungan: mau menindak tegas, tapi tak punya dalih sekuat saat masa Revolusi.
Secara global, Tiongkok mungkin tetap akrab dengan Uni Soviet. Hubungan mereka memang sempat retak, tapi tanpa Revolusi, perceraian ideologis mungkin tertunda. Sayangnya, ini juga berarti Tiongkok telat membuka diri pada Amerika Serikat.
Diplomasi legendaris antara Mao dan Nixon tahun 1972 bisa saja nggak terjadi, atau minimal baru digelar sepuluh tahun kemudian di kedai teh pinggir jalan, bukan di Great Hall of the People. Artinya, Tiongkok bakal lebih lama berada di pinggiran ekonomi dunia, dan mungkin melewatkan momentum emas integrasi global. Dunia juga bisa kehilangan momen viral saat presiden AS makan bebek Peking di Beijing.
Dampaknya terasa sampai ke akar rumput. Urbanisasi bisa terjadi lebih cepat tanpa redistribusi paksa ke desa-desa seperti dalam Revolusi. Tapi karena perencanaannya kacau, kota-kota besar bisa dipenuhi warga desa yang datang tanpa bekal dan harapan. Slum berkembang, kriminalitas meningkat, dan jalanan makin macet. Kalau kamu pikir kemacetan Jakarta itu parah, bayangkan kota Shanghai tahun 1985 dengan 20 juta orang yang semua merasa punya hak menyetir becak motor.
Tak hanya itu, gerakan mahasiswa pro-demokrasi yang baru muncul pada 1989 mungkin akan muncul lebih dini. Tanpa trauma Revolusi, anak muda mungkin lebih berani menyuarakan aspirasi politik sejak awal 70-an. Bisa jadi Tiongkok mengalami “Musim Semi Beijing” versi sendiri, jauh sebelum mereka meresmikan ponsel lipat.
Dan mari kita akhiri dengan satu skenario paling panas: Perang Vietnam. Karena Revolusi Kebudayaan membuat militer Tiongkok sibuk urus demo dan kampanye ideologis, mereka tidak bisa maksimal mendukung Vietnam Utara.
Tapi dalam semesta damai ini, Tiongkok mungkin terjun langsung ke medan perang. AS bisa menghadapi musuh tambahan yang bukan hanya tangguh, tapi juga penuh semangat revolusioner dan siap perang gerilya. Dunia bisa terguncang, dan sejarah Asia Tenggara akan ditulis ulang. Bahkan Hollywood mungkin harus bikin ulang Rambo agar lebih realistis.
Jadi, apakah dunia tanpa Revolusi Kebudayaan akan lebih baik? Jawabannya seperti nasi goreng tanpa kecap—tergantung selera. Revolusi ini jelas meninggalkan luka, tapi absennya juga berpotensi memicu kekacauan baru.
Sejarah bukan sekadar baik atau buruk, tapi sering kali soal pilihan-pilihan pahit yang dibungkus idealisme. Dalam kasus Tiongkok, revolusi bisa jadi seperti sambal: pedas, menyakitkan, tapi kadang dibutuhkan agar masakan tidak hambar.