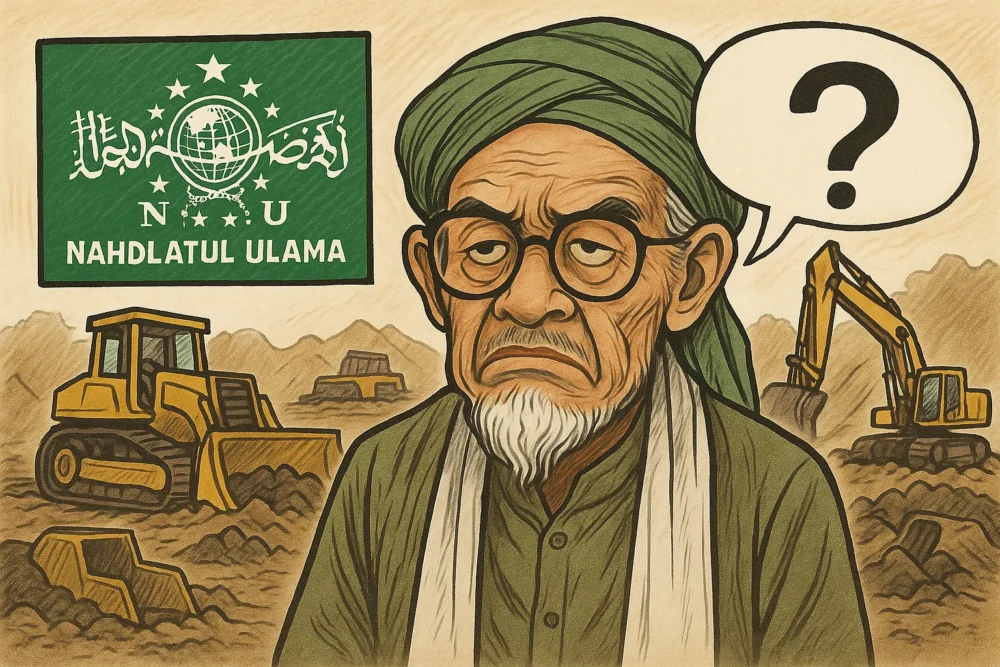Bayangkan suatu masa di mana demokrasi bukanlah tentang angka-angka kering di kotak suara, melainkan tentang duduk melingkar di bawah pohon beringin, secangkir teh hangat di tangan, suara gemericik sungai menemani obrolan tentang masa depan bersama.
Bung Karno, Ki Hajar Dewantara, dan Prof Soepomo pernah bermimpi seperti itu—sebuah sistem di mana petani, nelayan, seniman, dan guru punya kursi di meja kebijakan, bukan sekadar jadi angka dalam hitungan pemilu.
Mereka menyebutnya Golongan Karya: perwakilan yang lahir dari rahim nyata masyarakat, bukan dari mesin pencetak partai yang sibuk mengais donasi. Tapi, seperti kisah wayang yang dipelintir dalang tamak, mimpi indah itu berubah jadi lelucon pahit.
Golkar, yang awalnya dirancang sebagai antitesis partai politik—alat untuk memutus rantai oligarki—malah jadi monster yang melahap sendiri cita-citanya. Angkatan Darat, dengan seragam kebesaran dan senyum diplomatis, mengambil alih gagasan itu, mengubahnya jadi pisau bermata dua: satu sisi untuk menumpas komunisme, sisi lain untuk mengukuhkan kekuasaan.
Bung Karno mungkin mengira kolaborasi dengan Nasution adalah jalan damai, tapi sejarah membuktikan: ketika tentara dan politikus berbisik dalam satu kamar, yang lahir bukanlah kebijaksanaan, melainkan skenario power grab yang licin.
Tahun 1968, Golkar sudah berubah jadi kendaraan Orde Baru—mesin politik yang diisi BBM korupsi dan disopiri oleh para jenderal yang haus tahta. David Reeve, dalam bukunya, hanya bisa menghela napas: “Gagasan asli Golkar? Hilang, seperti garam dalam lautan.”
Dan kini, Golkar—yang dulu diidealkan sebagai wadah gotong royong—menjadi partai para pengusaha, di mana rapat pleno lebih mirip shareholders meeting ketimbang musyawarah rakyat. Ironis, bukan? Bung Karno pasti berguling di makamnya melihat anak kandung ideologinya dijual ke pasar saham. Tapi, inilah yang terjadi ketika demokrasi Barat—dengan logika winner takes all—menyusup ke sumsum politik kita.
Pancasila, yang seharusnya jadi roh Liebes Mitsein (kebersamaan penuh kasih), direduksi jadi jargon kampanye. Relasi “Aku-Engkau” ala Martin Buber—di mana manusia saling menghormati sebagai subjek setara—dikubur hidup-hidup, diganti jadi transaksi “Aku-Itu”: rakyat jadi objek, suara mereka dijual beli seperti komoditas di pasar gelap.
Kita bisa saja bertanya: “Kapan tepatnya musyawarah berubah jadi pertunjukan sulap, di mana suara rakyat menghilang dalam topi kotak suara?” Mungkin sejak kita terjebak dalam ilusi bahwa demokrasi adalah tentang frekuensi, bukan kualitas.
Pemilu diagungkan sebagai ritus suci, padahal dalam praktiknya, ia cuma pesta kostum mahal: caleg berpakaian safari keliling desa bagi-bagi sembako, buzzer upahan menari di medsos seperti dalang bayangan, dan rakyat—dengan hak pilih di tangan—dibius oleh janji-janji yang menguap sebelum pelantikan.
Pancasila, yang mestinya menempatkan manusia sebagai subjek yang utuh, terperangkap dalam kubangan pragmatisme. “Keadilan sosial?” Itu cuma jadi tulisan di uang pecahan sepuluh ribu, sementara di lapangan, yang kaya makin menggurita, yang miskin makin terhimpit di antara deru mesin kapital.
Tapi, ada secercah cahaya dalam kegelapan ini. Gagasan musyawarah mufakat tak pernah benar-benar mati—ia hanya tertidur, terpendam di balik gemuruh demokrasi elektoral. Bayangkan jika kita kembali ke akar: di mana keputusan tak diambil lewat adu jumlah suara, tapi lewat dialog yang merendah, di mana setiap “Aku” bersedia mendengar “Engkau” tanpa prasangka.
Seperti nenek moyang kita dulu, yang menyelesaikan sengketa tanah bukan lewat kuasa hukum tertulis, tapi lewat rembuk desa—duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sampai tercapai Gesamtperson, kebersamaan yang mengutamakan kebaikan bersama. Ini bukan utopia, melainkan memori kolektif yang bisa dihidupkan kembali.
Lihatlah bagaimana demokrasi Barat telah menggerus martabat kita. Pemilu langsung, yang konon puncak kedaulatan rakyat, justru melahirkan politikus yang lebih setia pada donatur ketimbang konstituen. Mereka sibuk mengurus pencitraan, mengubah medsos jadi panggung sandiwara, sementara petani yang kesulitan pupuk hanya jadi latar belakang foto kampanye.
“Keterwakilan golongan karya?” Itu cuma jadi hiasan di UUD, sementara di DPR, kursi didominasi oleh pengusaha dan mantan artis—yang pengetahuan mereka tentang sawah mungkin cuma sebatas filter Instagram.
Bung Karno pernah berteriak lantang: “Indonesia bukan bangsa yang mau jadi karbon copy bangsa lain!” Tapi kita, seperti anak kecil silau oleh mainan impor, tergopoh-gopoh mengekor sistem yang tak paham karakter kita.
Demokrasi ala Barat, dengan segala pilar dan prinsipnya, ibarat jas three-piece yang dipaksakan dipakai di tengah terik Jakarta—kelihatan mentereng, tapi bikin gerah dan tak nyaman. Sementara, demokrasi khas Nusantara—yang santun, mengutamakan dialog, dan berakar pada kearifan lokal—dianggap kuno, seperti keris yang disimpan di museum, dikagumi tapi tak pernah dipakai.
Mungkin sudah waktunya untuk berhenti berkaca pada Barat, dan mulai melihat ke dalam. Ketika musyawarah dihidupkan kembali, bukan sebagai ritual formal, tapi sebagai napas sehari-hari. Ketika keputusan tak lagi diambil lewat voting yang memecah belah, tapi lewat konsensus yang menyatukan.
Ketika Golongan Karya bukan lagi nama partai, tapi prinsip yang mengalir dalam darah: petani berbicara tentang pupuk, nelayan tentang laut, guru tentang pendidikan—semua duduk setara, tanpa dikotak-kotakkan oleh logika partai.
Dan di sini, di titik ini, kita bisa merasakan suatu kemungkinan—seperti angin sepoi yang tiba-tiba membelai wajah di tengah kemacetan. Kemungkinan bahwa demokrasi sejati bukanlah tentang pesta suara lima tahunan, tapi tentang bagaimana setiap hari, di warung kopi, di balai desa, di ruang-ruang kelas, kita belajar mendengar lagi. Bukan untuk menang, tapi untuk mengerti.
Bukan untuk kuasa, tapi untuk melayani. Seperti nasi liwet yang dimasak perlahan, demokrasi ala Indonesia takkan pernah instan—tapi ketika matang, aromanya akan memenuhi seluruh ruang, mengingatkan kita pada warisan yang nyaris terlupa: bahwa kita pernah punya cara sendiri, jauh sebelum Barat datang dengan kotak suara dan ilusi kebebasannya.
Jangan Biarkan Mereka yang Mencuri Mimpi.
Resep turun-temurun yang hanya perlu diaduk pelan, diberi kesabaran, dan dimasak dengan api kecil—sampai semua rasa menyatu, dan kita bisa menikmatinya bersama, tanpa ada yang merasa tercederai. Ku rasa kau tak belajar dari ajaran soekarno.