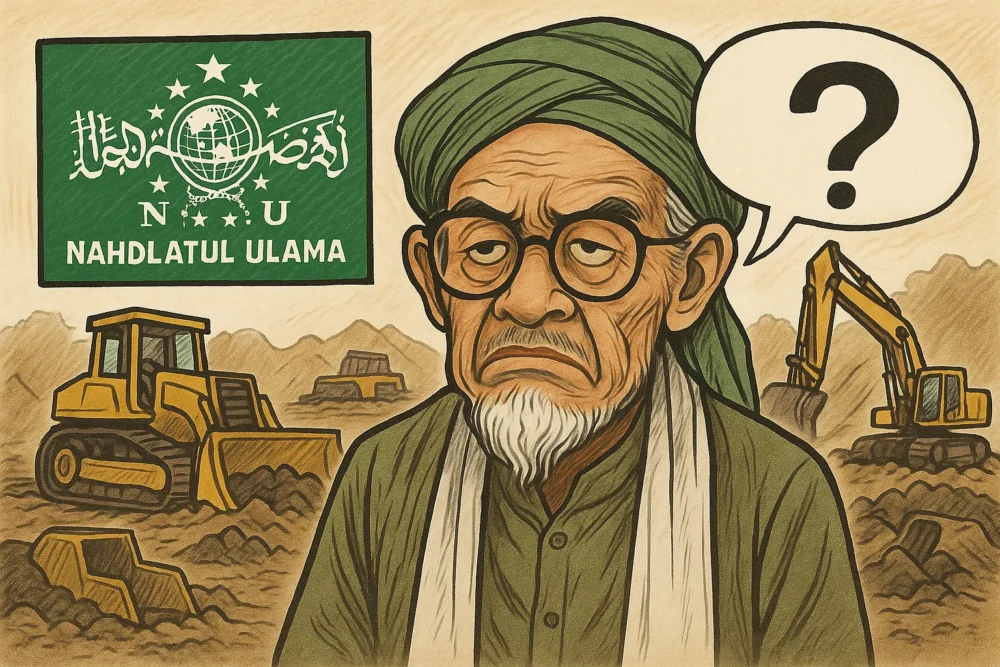Di antara debu jalanan kampus negeri yang atapnya bocor ketika hujan dan bau keringat dari kaos oblong yang dipakai tiga hari berturut-turut, aktivis mahasiswa Indonesia dari kalangan pas-pasan berjingkrak di atas panggung ironi bernama “perjuangan”.
Mereka berteriak “Reformasi Dikorupsi” sambil mengejar bus kota yang mogok, berdebat tentang teori postkolonial di warung kopi 10 ribu per gelas, lalu pulang ke kosan berukuran 3×3 meter yang dihuni lima orang—sebuah drama komedi-tragis yang membuat Sinetron Lorong jadi terasa seperti dokumenter National Geographic.
Adalah heroik melihat anak beasiswa KIP Kuliah menyanyikan “Darah Juang” dengan perut keroncongan, sambil berharap katering demo menyisakan nasi bungkus berlauk tempe? atau setidaknya bagi korlap bisa bangun relasi saat audiensi. Polanya masih sama, aksi, audiensi, dan subsidi. Data fiktif dari riset dadakan menyebut 99% aktivis dari keluarga miskin lebih paham jadwal bagi-bagi sembako ketimbang jadwal kuliah, karena urusan perut selalu lebih revolusioner daripada teori Foucault.
Lagu-lagu perjuangan seperti “Totalitas Perjuangan” bergema dari ponsel pintar bekas yang layarnya retak, diiringi bunyi “ting-ting” notifikasi pengingat tagihan kosan. Mereka menyanyikan “Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan” dengan suara sumbang, sementara kejayaan yang sesungguhnya mereka rindukan adalah lulus tepat waktu biar beasiswa nggak dicabut.
Tak ada bedanya menyanyikan lagu revolusi di depan gedung DPR dengan melantunkan dangdut di angkringan. Sama-sama menghibur, sama-sama tidak didengar penguasa, dan sama-sama berakhir dengan suara serak karena kurang minum air gratis.
Setiap kali kata “revolusi” disebut dalam rapat organisasi, satu anggota harus keluar dadakan karena telepon dari orang tuanya berbunyi “maaf bulan ini belum bisa kirim uang”. Spanduk bertuliskan “Tolak Komersialisasi Pendidikan” dicoret-coret pakai spidol yang dicuri dari ruang dosen, digantung pakai tali jemuran yang sudah reyot.
Demikian semiotika perlawanan ala mahasiswa minim budget adalah tontonan absurd yang layak jadi konten TikTok.
Bukankah filosofis melihat spanduk anti-kapitalisme dibuat dengan bahan seadanya sambil ngutang ke warung sebelah kosan? Bahasa perlawanan mereka adalah dialek campuran antara istilah kiri radikal dan slang pasar tradisional: “Hegemoni negara harus di-dekonstruksi biar kita bisa dapet kuota Bansos tambahan!“.
Ketika diminta jelaskan arti “alienasi buruh”, mereka akan menunjuk tukang bakso langganan yang dagangannya digusur preman—sebuah pembelajaran empiris yang tak tercantum di modul kuliah.
Paradoks terbesar terjadi ketika semester akhir tiba. Aktivis yang dulu bersumpah “tak akan menjual idealisme” tiba-tubah menjadi calon PNS yang rajin ikut bimbel tes CPNS, sambil berbisik: “Apa artinya melawan sistem kalau nggak bisa bayar utang ke koperasi kampus?”.
Apa gunanya teori Antonio Gramsci jika tak bisa menjawab soal tes wawasan kebangsaan? Data fiktif dari LSM Gadungan menyebut 80% mantan aktivis miskin akan menghapus semua status demo dari Facebook dalam 24 jam setelah lulus, menggantinya dengan permohonan kerja: “Fresh graduate siap ditempatkan di mana saja. Gaji penting, pengalaman lebih penting. Bisa mengoperasikan Excel.”
Aktivisme ala anak kos adalah seni bertahan hidup yang dipoles jargon-jargon mentereng. Rapat koordinasi digelar sambil menyelundupkan nasi kotak dari acara seminar kampus, strategi penggalangan dana direncanakan sambil mengumpulkan botol bekas untuk ditukar ke pengepul.
Bukankah revolusioner, mengumpulkan dana demo dari hasil jualan pulsa elektrik ke teman sekelas? Mereka dengan bangga menyebut ini “crowdfunding proletar”, meski uang yang terkumpul cuma cukup untuk beli spanduk vinil tipis yang sobek diterpa angin saat demo.
Konflik kelas dalam gerakan mahasiswa miskin adalah lelucon pedas. Anak penerima BPNT berdebat dengan anak KIP Kuliah tentang strategi melawan kemiskinan, sementara keduanya sama-sama menunggu salaman amplop dari pejabat yang mereka sebut koneksi.
Berkoar tentang upah buruh jika untuk beli pulsa saja harus ngutang dulu dan mereka mengecam korupsi Bansos sambil berharap dapat jatah jadi petugas Bansos atau setidaknya mengadvokasi agar bapak-ibunya dapat jatah sembako dari caleg dan ini adalah sebuah kontradiksi yang lebih rumit daripada soal matematika ekonomi makro.
Aktivisme digital ala generasi micin adalah adaptasi kreatif keterbatasan. Live TikTok dari lokasi demo diisi dengan permohonan: “Yang di rumah boleh transfer ke Dana 081xxxx buat beli air mineral ya, panas banget di sini!”.
Infografis tentang kenaikan BBM didesain pakai Canva gratisan dengan template “Sale Promotion”, karena paket premium terlalu mahal. Mereka sudah merasa paling pejuang.
Bukankah cerdas menggunakan kuota internet pakai Tunnel SSH dari program “Kuota Murah Pendidikan” untuk mengkritik kebijakan pendidikan? Mereka menyebut ini “hack sistem”, meski ujung-ujungnya tagihan listrik kosan telat dibayar karena uang dipakai buat print makalah kopasan tentang keadilan sosial.
Proses kooptasi mantan aktivis miskin ke dalam sistem adalah sinetron yang episodenya berulang. Mereka yang dulu teriak “Reformasi Total” kini jadi relawan parpol yang dibayar 50 ribu per jam plus nasi bungkus, berkilah “Ini taktik infiltrası”.
Apa bedanya jadi buzzer politik dengan jadi aktivis jalanan jika sama-sama pakai kata-kata bombastis, bedanya yang satu dibayar via transfer bank, yang lain dibayar dengan janji “nanti kalau menang, kamu jadi staf ahli”.
Mantan ketua BEM yang dulu demo anti-kenaikan Uang Kuliah kini jadi panitia penerimaan mahasiswa baru, sibuk menjual “modul sukses masuk kampus” ke adik kelas, sungguh ironi yang lebih pahit dari kopi tubruk tanpa gula.
Universitas-universitas negeri telah menjadi panggung sandiwara kemiskinan intelektual. Mata kuliah kewirausahaan diajarkan dosen yang gajinya telat tiga bulan, menghasilkan lulusan yang fasih teori enterpreneurship tapi bisnisnya cuma jualan pulsa di kantin.
Bukankah tragis melihat anak penerima KIP Kuliah diajarkan cara membuat start-up tech sementara laptopnya hanya bisa dipakai buat ngetik di Microsoft Word? Perpustakaan kampus yang bukunya terbitan 1990-an menjadi saksi bisu debat-debat panas tentang masa depan Indonesia, sementara masa depan mereka sendiri masih digadaikan ke ‘rentenir’ biar bisa bayar SPP.
Gerakan mahasiswa miskin adalah festival ironi harian. Mereka demo menuntut transparansi anggaran kampus sementara tagihan listrik indekosnya belum lunas tiga bulan. Membuat poster “Tolak Pembangunan Mal” di atas kardus bekas mi instan, sambil berharap suatu hari bisa belanja di mal tersebut pakai gaji pertama.
Bukankah tragikomedi melihat spanduk “Lawannya Oligarki” dicat pakai kuas yang bulunya sudah rontok, dibeli dari toko bangunan yang dimiliki konglomerat? Mimpi mereka tentang keadilan sosial bersaing keras dengan mimpi membeli kipas angin kedua biar nggak gerah di kamar kos.
Solusi-solusi yang ditawarkan sering berakhir jadi lelucon kelam. “Membangun aliansi dengan buruh” artinya magang di pabrik sepatu selama liburan buat nambah uang saku. “Pendidikan politik kerakyatan” berarti ngajari ibu-ibu PKK cara klaim BPJS sambil numpang makan siang di rumah mereka.
Bukankah revolusioner, mengadakan sekolah alternatif untuk anak jalanan pakai fasilitas wifi gratisan dari kedai kopi tetangga? Pelatihan advokasi biasanya berakhir dengan peserta pulang cepat karena sudah dapat jatah makan dan sertifikat.
Fenomena eks aktivis yang jadi pengusaha “startup sosial” adalah parodi modern. Mereka yang dulu demo anti-Google Classroom kini membuat aplikasi bimbel online dengan jargon “Pendidikan untuk Rakyat”, tapi tarifnya mahal.
Apa bedanya start-up mereka dengan korporasi yang mereka kritik? Sama-sama cari untung, bedanya start-up mereka pakai font warna merah dan gambar kepalan tangan di logo. Mantan aktivis yang dulu teriak “Digitalisasi adalah bentuk penjajahan baru” kini jadi content creator TikTok Shop, menjual kaos bertuliskan “Rebel Spirit” produksi pabrik garmen upah murah.
Di tengah semua ironi ini, gerakan mahasiswa miskin tetap menjadi pertunjukan paling otentik. Mereka adalah cermin retak generasi yang terpaksa jadi idealis karena tak punya pilihan lain. Mungkin kita perlu lagu baru berjudul “Indomie Perjuangan” yang menceritakan heroisme bertahan hidup dengan uang 10 ribu sehari.
Sampai saat itu tiba, utopia reformasi akan tetap menjadi dongeng yang diceritakan sambil membodohi kader-kadernya dengan idealisme yang lebih penting daripada kemandirian finansial, di sela-sela menghitung hari sampai tanggal cairnya beasiswa.
Dalam epilog yang tak pernah ditulis, aktivisme mahasiswa miskin mungkin adalah puisi epik yang ditulis di kertas bekas kuitansi fotokopian. Sebuah kisah tentang lilin yang mencoba menerangi kegelapan sambil takut kehabisan sumbu, tentang teriakan yang tenggelam dalam deru mesin generator kosan, tentang mimpi-mimpi yang digadaikan ke rentenir tapi tetap tak mati-mati.
Di ujung semua ini, yang tersisa mungkin hanya tawa getir: bagaimana seluruh sistem pendidikan tinggi dibangun di atas kontradiksi, dimana para penjaga gawang gerbang pengetahuan itu sendiri harus berjibaku melawan rasa lapar sambil memikul beban jadi “agen perubahan”.
Tapi seperti kata pepatah kuno di kalangan aktivis kosan: “Lebih baik suara serak karena demo daripada serak karena nangis minta uang ke orang tua”.
Untuk para aktivis sejati yang masih bertahan—kalian ada, kan?